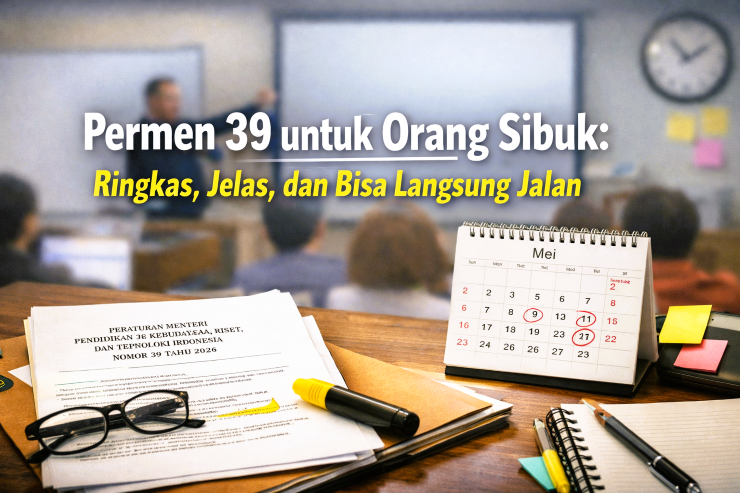Tanpa Motivasi, Permen 39/2025 Hanya Jadi Dokumen
Tanpa Motivasi, Permen 39/2025 Hanya Jadi Dokumen Permen 39 Tahun 2025 sudah resmi berlaku.Pasalnya jelas, strukturnya rapi, maksudnya pun baik. Tapi seperti banyak aturan lain, pertanyaan pentingnya bukan lagi apa isinya, melainkan bagaimana ia dijalankan. Di kampus, tidak semua aturan gagal karena desainnya keliru.Namun banyak aturan kehilangan daya ubah ketika dijalankan setengah hati. Dipatuhi, tapi […]
Tanpa Motivasi, Permen 39/2025 Hanya Jadi Dokumen Read More »